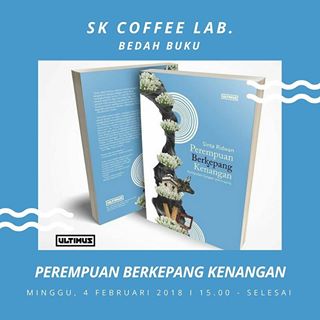Sastra (dalam hal ini cerpen) tak harus dibebani sebagai muatan. Biarlah ia mempertahankan eksistensinya sebagai ruang antara, antara fakta dan fiksi. Mungkin seperti itu juga kenangan bekerja, entah terbuat dari apa.

“Terbuat dari apakah kenangan?” demikian pertanyaan Seno Gumira Ajidarma dalam sebuah cerita. Kenangan bisa jadi entitas yang utuh dan sangat personal. Bisa membentuk seseorang sekaligus bisa menghancurkan seseorang di masa kekiniannya. Bagi seorang penulis dan “pelamun” kenangan bisa jadi semesta sebelah yang bisa kita kunjungi setiap saat. Dan agaknya, Sinta Ridwan melakukannya.
Kenangan itu dibekukan dalam kepang rambut yang tersimpan di dalam kotak, puluhan tahun lamanya. “Harum kemirinya pun masih tercium,” demikian petikan kalimat dalam cerpen yang sekaligus menjadi judul buku ini “Perempuan Berkepang Kenangan”
Narasi dibangun ketika si aku ini menyusuri kisah Abah Rivai dan istrinya, Abah Bojong, pasangan hidup yang saling setia dari masa muda hingga akhir hayat. Kisah ini dituturkan melalui tokoh Mamih, yang bersentuhan dengan Abah Rivai dan Abah Bojong semasa hidupnya karena dia anak asuhnya.
Menjadi bukan sekadar kisah romantika ketika penulis menyisipkan kematian Abah Rivai karena sengketa politik, DI/TII meski tidak dijelaskan benderan di sana. Pembaca diajak untuk menyusuri bagaimana sebuah penantian di masa lalu akan tetap menjadi penantian di masa depan ketika ada yang masih membekukan dalam ingatan.
Ada 10 cerita dalam buku ini, temanya berbeda-beda pun setting-nya. Latar belakang penulisnya sebagai pejalan (dalam arti berpindah satu tempat ke tempat lain) dan pejalan dalam arti petualang imajinasi dapat saya rasakan ketika membaca cerpen demi cerpennya.
Selain itu, cerita-cerita ini menjadi “berasa” ketika diksi yang disajikan memang dipilih dengan cermat, atau tepatnya dipungut dengan hati-hati di sepanjang perjalanan. Sehingga pembaca diajak untuk melangkah perlahan dari satu kata ke kata lain.
Kebetulan, mungkin karena saya juga penyuka cerpen-cerpen yang tak hanya mementingkan perkara yang disajikan tetapi juga para pemilihan kata. Bagi yang suka “gaya realis” katakan seperti novel Michael Crichton atau Stephen King dan tak menikmati jenis lain, akan kurang bisa menikmati gaya penulisan yang seperti Sinta hadirkan.
Ini bukan persoalan baik buruk, lebih berkelas atau tidak. Sebab membaca karya sastra tentu bukan untuk menghasilkan strata, tetapi saya kira lebih dari itu. Untuk memberi ruang kita untuk senyap dan berdialog dengan diri sendiri.
Hal itu juga disajikan penulis dalam “Cerita Tanpa Judul” (halaman 23). Jika yang suka dengan alur maju dan harus ada klimaks dari sebuah cerita lalu menurun, tidak akan menemukan di sini. Kita “hanya” akan diajak bermain-main dengan pemikiran. Memerhatikan pohon dan dedaunan di “hutan tersembunyi seperti tidak tidak ingin ditemui orang lain”. Saya suka kalimat ini. Seperti yang saya katakan di depan, pemilihan kata yang cermat.
Juga pada “Senja di Montmartre”. Memang ada alurnya, ada tokohnya, hanya kita diajak masuk ke dalam ruang pemikiran “si aku” ini untuk meraba senja di kota para seniman itu.
Tentang “si aku”
Dalam ruang iseng yang memotret sebuah karya bukan hanya sebagai karya tetapi terkait dengan penulisnya, maka kita kerap akan bertanya-tanya seperti apa realitasnya? Apalagi ketika penulis mengambil sudut orang pertama (aku) apakah akan selalu menjadi tokoh yang sesungguhnya?
Di beberapa sisi, pengambilan sudut pandang orang pertama akan memudahkan dalam membangun cerita. Pun dari sisi pembaca, akan merasa lebih dekat dengan apa yang ingin disampaikan.
Dalam buku ini, saya tidak ingin “menuduh” bahwa ini pengalaman nyata atau hanya tumbuh dalam imajinasi dan alterego. Bukan persoalan itu ketika membaca. Hanya penulis berhasil membangun kosistensi karakter tokoh si aku (meski kemudian namanya menjadi sama, Sita), dari awal sampai akhir selalu mirip untuk tak mengatakan sama.
Selain itu, belakang penulis yang suka melakukan perjalanan dan perempuan juga seperti tokoh cerita, akan memperkuat ruang iseng ini.
Tidak perlu juga ditanyakan, yang jelas apa yang disampaikan dalam setiap cerita ini, kerap tersisip kegelisahan yang ingin disampaikan meski tak harus dimengerti apalagi diikuti. Saya berpendapat bahwa sastra (dalam hal ini cerpen) tak harus dibebani sebagai muatan. Biarlah ia mempertahankan eksistensinya sebagai ruang antara, antara fakta dan fiksi. Mungkin seperti itu juga kenangan bekerja, entah terbuat dari apa.
Selamat bertualang!
Disampakaikan dalam bedah buku “Perempuan Berkepang Kenangan”
SK Coffee Lab, Kediri, 4 Februari 2018

PEREMPUAN BERKEPANG KENANGAN
Kumpulan Cerpen 2011-2015
@Sinta Ridwan
Penyunting : Jia Effendie
Pengantar : Berto Tukan
Ilustrasi Isi dan Sampul : Aldian Yodha Karunia
Desain Sampul : Heri H. Subandi
Proofreader : Sangdenai, Syahar Banu
Penerbit : Ultimus Bandung
Tahun : 2017
Halaman : xviii + 198 hlm, 11,5 x 17,5 cm
ISBN : 978-602-8331-97-5